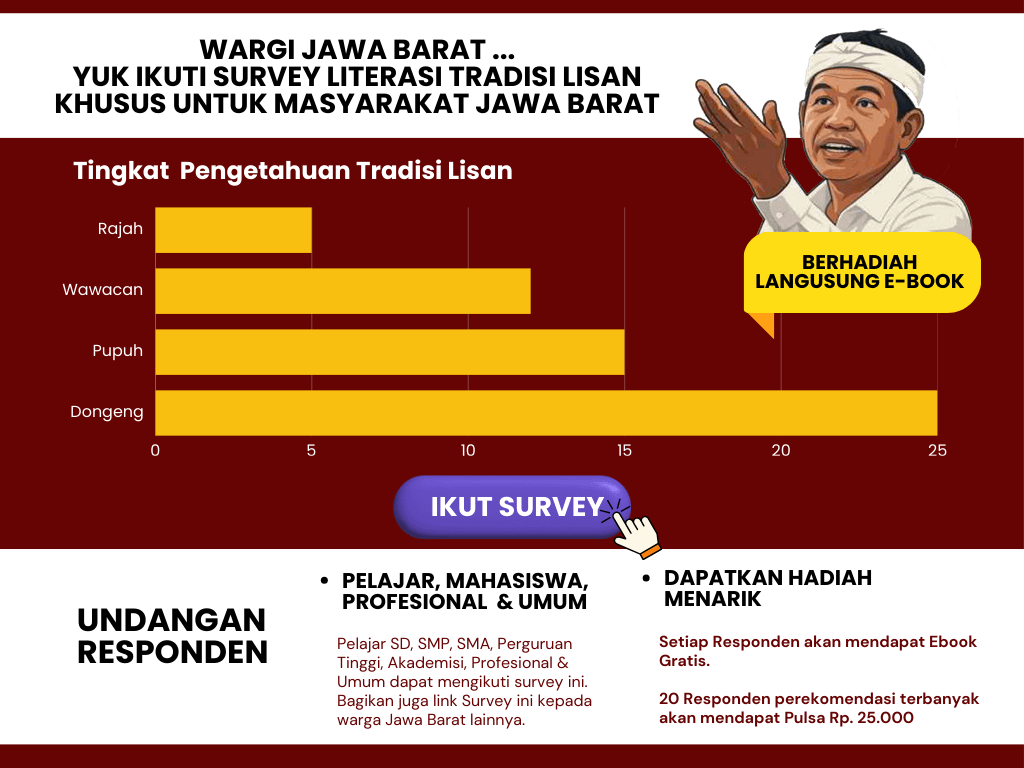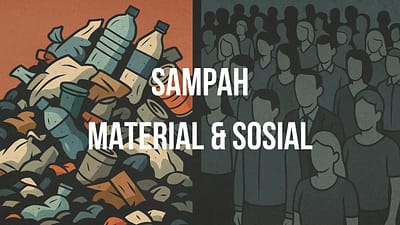SinergiNews – OPINI. Pernyataan Menteri ATR/BPN bahwa “tanah tidak ada yang memiliki, yang memiliki tanah itu negara” merupakan sesuatu yang lebih besar dari kebijakan teknis. Pernyataan itu lebih kepada deklarasi filosofis yang secara radikal membalikkan relasi konstitusional antara negara dan rakyat.
Klaim yang bersandar pada pembacaan literal Pasal 33 UUD 1945 ini, mengabaikan roh konstitusi yang menempatkan negara sebagai pengatur (beheersrecht), bukan pemilik (eigendomsrecht). Kekeliruan epistemologis ini berbahaya karena meminggirkan hak kultural masyarakat adat dan berpotensi mengulangi kesalahan historis domeinverklaring, kebijakan kolonial Belanda tahun 1870 yang mengklaim semua tanah tak bertuan sebagai milik negara.
Sejarawan hukum Cornelis van Vollenhoven dalam Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (1918) mencatat bahwa praktik inilah yang memicu 73% konflik agraria di era kolonial. Ironisnya, setelah satu abad, negara merdeka justru mengadopsi logika yang sama melalui jargon “penguasaan negara”.
Padahal, Boedi Harsono (arsitek UUPA 1960) menjelaskan dalam otobiografinya Hukum Agraria Indonesia (2008) bahwa Pasal 33 UUD 1945 dirancang sebagai amanat pengelolaan, bukan sertifikat kepemilikan. Ketika pejabat publik melupakan sejarah ini, mereka menghidupkan kembali hantu feodalisme di mana negara bertindak sebagai tuan tanah, sementara rakyat direduksi menjadi penyewa di negeri sendiri.
Bahaya klaim ini semakin nyata dalam konteks masyarakat adat. Antropolog James C. Scott dalam The Art of Not Being Governed (2009) menunjukkan bahwa konsep kepemilikan tanah secara komunal-transendental telah hidup ribuan tahun sebelum negara modern lahir.
Di Mentawai, tanah disebut uma (ruang hidup holistik yang mencakup hutan, sungai, dan kubur leluhur), sementara di Bali dikenal tanah ayahan desa (milik kolektif desa adat). Penyederhanaan hak ulayat menjadi sekadar “hak pakai” yang bisa dicabut negara merupakan bentuk epistemicide (pembunuhan pengetahuan lokal), se bagaimana dikritik Boaventura de Sousa Santos (2014).
Dengan demikian, pernyataan menteri bukan hanya keliru secara hukum, melainkan juga pengkhianatan terhadap jiwa UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Sebagaimana diingatkan Mohammad Hatta dalam risalah sidang BPUPKI 1945: “Negara lahir untuk melindungi bumi rakyat, bukan merampasnya.”
Kekeliruan Epistemologi, Dekonstruksi Makna “Penguasaan Negara”
Klaim kepemilikan mutlak negara atas tanah merupakan kesalahan epistemologis yang berakar pada pembacaan dangkal terhadap Pasal 33 UUD 1945. Boedi Harsono (2008), arsitek UUPA 1960, dengan tegas menjelaskan bahwa frasa “dikuasai negara” dalam kerangka hukum agraria nasional merupakan terjemahan konseptual dari beheersrecht (hak mengatur), bukan eigendomsrecht (hak kepemilikan).
Distingsi filosofis ini termanifestasi secara konkret dalam konstruksi hierarkis hak atas tanah menurut UUPA No. 5/1960, di mana Hak Milik (Pasal 20) menempati posisi puncak sebagai hak perseorangan yang bersifat turun-temurun (erfelijk), terkuat (sterkste recht), dan tetap (duurzaam). Sifat hak ini hanya dapat hapus melalui dua mekanisme terbatas: pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 dengan syarat kepentingan umum dan ganti rugi layak, atau pelepasan sukarela oleh pemegang hak, sebuah konstruksi hukum yang secara diametral membantah klaim kepemilikan mutlak negara.
Penguatan atas posisi kedaulatan hukum privat ini kemudian dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang secara konstitusional menegaskan bahwa “Hak Milik atas tanah merupakan hak konstitusional warga negara… Negara hanya berwenang mengatur (regelendaad), bukan memiliki (eigendomsrecht)”.
Putusan landmark ini sekaligus menolak konsep domeinverklaring, warisan hukum kolonial yang memberi negara hak kepemilikan absolut atas tanah tak bertuan, sebagai institusi yang bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Lebih lanjut, pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam Pasal 18B UUD 1945 bersifat self-executing, tidak memerlukan regulasi turunan untuk berlaku efektif.
Sebagaimana didokumentasikan Van Vollenhoven (1918) dalam kajian adat kolosalnya, tanah ulayat bersifat komunal-transendental: suatu bentuk perwalian antargenerasi (intergenerational trusteeship) di mana masyarakat adat berperan sebagai penjaga, bukan pemilik absolut. Pengabaian hak ini tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga Konvensi ILO 169 Pasal 14 tentang traditional land tenure yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19/2013.
Klaim kepemilikan mutlak negara justru melahirkan kontradiksi internal dalam tubuh UUPA itu sendiri. Di satu sisi, Pasal 9 UUPA menyatakan hak atas tanah “berasal dari hak bangsa Indonesia”, menegaskan asal-usul kolektif hak penguasaan.
Namun di sisi lain, Pasal 21(1) mengizinkan alih kepemilikan Hak Milik kepada warga negara asing, sebuah kemustahilan logis jika negara benar-benar pemilik tunggal. Lebih ironis lagi, sementara Penjelasan UUPA menekankan prinsip fungsi sosial tanah yang mengatasi kepentingan individu, Pasal 6 secara tegas mewajibkan negara mengakui hak-hak adat.
Paradoks hukum ini mengungkap kegagalan epistemik: bagaimana mungkin negara sebagai “pemilik mutlak” diwajibkan mengakui hak yang secara filosofis ia klaim tidak ada? Kontradiksi ini membuktikan bahwa klaim kepemilikan mutlak merupakan penyimpangan dari roh UUPA yang justru didesain untuk melindungi hak-hak substantif rakyat atas tanah.
Antropologi Kepemilikian, dari Leluhur ke Epistemisid.
Pernyataan pejabat bahwa “Mbah-mu tidak bisa membuat tanah” bukan hanya kesalahan faktual, melainkan manifestasi kebutaan epistemologis terhadap ontologi tanah dalam masyarakat agraris Nusantara. Antropolog Roy Ellen (1986) dalam penelitiannya di Timor menunjukkan tanah bukan benda mati melainkan dosa aan (ibu bumi), entitas hidup yang bernapas melalui relasi kosmologis antara leluhur, manusia, dan alam semesta. Klaim negara sebagai “pemilik tanah” sama absurdnya dengan mengklaim kepemilikan atas langit atau laut, karena tanah dalam kosmologi lokal adalah subjek yang memiliki manusia, bukan objek yang dimiliki.
Mekanisme pewarisan tanah justru membuktikan bagaimana otoritas leluhur mengatasi klaim negara modern. Franz von Benda-Beckmann (1999) mengungkap sistem pusako tinggi di Minangkabau: tanah ulayat diwariskan melalui ritual batagak panghulu (pelantikan kepala adat oleh ninik mamak), penegakan gala-gala (sanksi adat bagi pelanggar batas), dan transfer sako (otoritas spiritual pengelolaan).
Proses sakral ini, yang bisa memakan 7 tahun untuk satu siklus pewarisan, menegaskan bahwa negara tak pernah “memberi” hak, melainkan hanya mengakui sistem yang telah berjalan ribuan tahun. Pengakuan ini bersifat deskriptif, bukan konstitutif.
Penyangkalan negara terhadap relasi leluhur-tanah merupakan bentuk epistemicide (pembunuhan pengetahuan lokal) sebagaimana dikonseptualisasikan Boaventura de Sousa Santos (2014). Di Sumba, tanah tana marapu (tanah leluhur suci) menjadi pusat ritual pasola di mana masyarakat menyembelih 200 kuda sebagai persembahan untuk mempertahankan hubungan dengan arwah nenek moyang. Ketika negara menyatakan “leluhur tidak membuat tanah”, ia melakukan kekerasan simbolik (Bourdieu) yang memutus collective memory, suatu bentuk kolonisasi kesadaran yang lebih berbahaya daripada pendudukan fisik.
Lebih dalam lagi, tanah berfungsi sebagai arsitektur identitas yang menyusun cara berpikir kolektif. Clifford Geertz (1963) membuktikan bagaimana masyarakat Jawa memaknai tanah sebagai simbol kesinambungan darah dan sejarah: kepemilikan sawit warisan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bukti eksistensi garis keturunan yang menghubungkan mbah buyut hingga cucu wayah.
Bagi Suku Dayak Iban di Kalimantan Barat, tanah pusaka disebut tanah pengurip (tanah kehidupan), suatu konsep sakral di mana setiap jengkal humus mengandung jiwa leluhur yang mengawal siklus pertanian. Logika produktivitas kapitalistik yang menganggap lahan tak ditanami sebagai “nganggur” sama sekali mengabaikan dimensi kronos (waktu sakral) dalam kebudayaan agraris.
Ironisnya, kekerasan epistemik ini justru terjadi di ruang di mana negara seharusnya menjadi penjaga keberagaman. Ketika administrasi pertanahan memaksa masyarakat adat membuktikan kepemilikan dengan sertifikat, sebuah dokumen yang asing bagi sistem panili (tanda batas tradisional Bugis) atau doro-dodara (penanda alam Togutil), negara secara tak sadar mengulangi praktik domeinverklaring kolonial yang dulu merampas tanah dengan dalih “terra nullius”. Padahal, sebagaimana diingatkan James C. Scott (2009), pengetahuan lokal tentang pengelolaan tanah justru sering lebih berkelanjutan secara ekologis daripada skema modern yang dipaksakan negara.
Filsafat Kenegaraan, Kedaulatan Rakyar sebagai Poros
Klaim kepemilikan absolut negara atas tanah tak ahanya menjadi kesalahan dalam persepsi hukum, melainkan pembalikan logika kenegaraan modern yang melakukan patenisasi relasi kuasa. Dekonstruksi teori kontrak sosial menjadi titik tolak kritis: John Locke dalam Second Treatise of Government (1689) Pasal 123-124 menegaskan bahwa “tujuan utama bersatunya manusia dalam negara persemakmuran adalah pelestarian hak milik”.
Pernyataan ini menegaskan negara lahir dari konsensus warga (civil society) untuk melindungi hak properti, bukan menciptakannya. Hak properti bersifat pre-political, eksis sebelum negara terbentuk. Dengan mengklaim diri sebagai “pemilik tanah”, negara justru berubah menjadi perampas hak natural yang seharusnya dilindunginya, sebuah ironi yang mengembalikan manusia ke state of nature yang chaos.
Jean-Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social (1762) Buku I Bab VI lebih radikal: “Kedaulatan tidak dapat diwakili […] ia terletak pada kehendak umum (volonté générale)”. Klaim kepemilikan negara merupakan pengkhianatan terhadap prinsip ini karena dua alasan mendasar: pertama, ia mengalihkan sovereign will (kehendak berdaulat) menjadi state possession (kepemilikan negara); kedua, ia mengubah rakyat dari pemilik kedaulatan menjadi sekadar penyewa di tanahnya sendiri. Transmutasi ini membajak esensi kedaulatan rakyat menjadi alat legitimasi kekuasaan vertikal.
Konstitusi Indonesia merupakan manifestasi nyata prinsip kedaulatan rakyat ini. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia “berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada […] keadilan sosial”.
Kalimat ini harus dibaca sebagai penegasan ganda: sebagai deklarasi asal-usul negara bahwa negara adalah creature rakyat, bukan sebaliknya; dan sebagai hierarki normatif bahwa kedaulatan rakyat menempati posisi tertinggi, di atas negara, yang kemudian mengatur tanah.
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (“Kedaulatan berada di tangan rakyat”) menjadi anti-tesis langsung klaim kepemilikan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 memperkuat tafsir ini dengan menegaskan bahwa “kedaulatan rakyat berarti negara tak boleh merampas hak dasar warga tanpa mandat konstitusional”.
Konsep “dikuasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 hanya bermakna sebagai amanat fidusia (trusteeship). Negara berposisi sebagai trustee yang mengelola tanah untuk kepentingan beneficiary (rakyat), bukan sebagai pemilik. Ini merupakan hak administratif (imperium), bukan hak kepemilikan (dominium).
Filsuf kenegaraan Indonesia, Soepomo, dalam Risalah BPUPKI (1945) menjelaskan orientasi ini: “Kekuasaan negara bersifat sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa mutlak”. Amanat fidusia ini menjadi benteng terhadap transformasi negara menjadi Leviathan dalam terminologi Thomas Hobbes, monster politik yang melahap kedaulatan rakyat.
Ketika negara mengklaim diri sebagai “pemilik tanah”, ia menciptakan relasi tuan-hamba (Herrschaft-Knechtschaft) ala Hegel: negara menjadi tuan (Herr) yang menguasai kepemilikan mutlak, sementara rakyat direduksi menjadi hamba (Knecht) yang hanya “dihibahkan” hak pakai.
Padahal, Pasal 33 UUD 1945 dirancang untuk mencegah feodalisme baru, bukan melestarikannya. Klaim ini merupakan pembajakan mandat konstitusional karena tiga alasan fundamental: pertama, ia mengosongkan makna Pasal 33 dengan mengubah “penguasaan untuk kemakmuran rakyat” menjadi “penguasaan untuk kekuasaan negara”; kedua, ia melanggar Pasal 28D(1) tentang hak milik sebagai hak konstitusional; ketiga, ia menyubversi demokrasi dengan menghidupkan kembali logika domeinverklaring, warisan kolonial yang telah dikubur oleh UUPA 1960.
Pada akhirnya, klaim kepemilikan negara atas tanah adalah pengkhianatan terhadap janji konstitusi: bahwa tanah adalah ruang hidup rakyat, bukan properti kekuasaan. Sebagaimana api tidak boleh menjadi pemilik kayu bakar, negara tidak boleh menjadi tuan atas ruang hidup yang dipercayakan rakyat kepadanya.
Ketika pejabat menyatakan “tanah milik negara”, ia sedang membunuh roh konstitusi. Negara tak lebih dari konsultan pengelola tanah yang diamanatkan rakyat. Klaim kepemilikan mutlak adalah pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang mengubah republik menjadi kerajaan feodal baru.
Diskriminasi Sistemik, Bias Kekuasaan dalam Eksekusi
Anatomi ketimpangan kebijakan pertanahan Indonesia termanifestasi dalam pola diskriminasi struktural yang menganga. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2024 mengungkap 672 konflik agraria sepanjang 2023 dengan total luasan 520.491 hektar, bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti kegagalan epistemik kebijakan negara.
Mayoritas konflik ini bersumber dari penerapan selektif klaim “lahan nganggur” yang secara represif menyasar kelompok rentan sambil melindungi kekuatan modal. Mekanisme diskriminasi ini berlapis tiga: bias kelas yang menjadikan petani gurem pemilik lahan di bawah 0,5 hektar sebagai korban utama penyitaan tanpa verifikasi ekologis; bias kultural yang memaksa masyarakat adat membuktikan kepemilikan melalui administrasi modern yang mengabaikan sistem pengetahuan lokal; serta bias kekuasaan yang memperlakukan korporasi pemegang 3,2 juta hektar lahan idle (KLHK, 2024) dengan sekadar surat teguran.
Matriks kekuasaan dalam eksekusi kebijakan ini memperlihatkan asimetri perlindungan hukum yang tajam. Di satu sisi, petani kecil menghadapi proses penyitaan ekstrajudisial melalui intimidasi aparat tanpa ganti rugi memadai, sebagaimana didokumentasikan Indonesian Center for Environmental Law (2023).
Di sisi lain, korporasi menikmati privilege hukum melalui perisai legal perjanjian investasi, restrukturisasi izin otomatis (perpanjangan HGU), dan kemampuan melancarkan class action ketika terancam sanksi. Ironi regulasi semakin nyata dalam Peraturan Menteri ATR No. 18/2021: meski mensyaratkan “ketidakterlibatan masyarakat lokal” sebagai indikator lahan idle, Pasal 15(3)-nya mengabaikan faktor penghambat akses seperti keterbatasan infrastruktur dan modal. Sementara itu, Pasal 22 memberi kelonggaran rehabilitasi dua tahun bagi korporasi, fasilitas yang tidak tersedia bagi petani tradisional.
Fenomena kekerasan birokratik yang dikonseptualisasikan Max Weber dalam Wirtschaft und Gesellschaft (1922) menjelaskan mengapa birokrasi beroperasi secara instrumental-rasional. Logika birokrasi mereduksi tanah menjadi sekadar “objek administratif” yang diukur melalui indikator kuantitatif semu, kepemilikan sertifikat atau catatan produksi, sambil menghilangkan konteks substantif.
Tanah bera (masa istirahat ekologis) dicap “menganggur”, lahan ritual adat dianggap “tak produktif”, dan sistem wanatani kompleks direduksi menjadi “tak terkelola”. Dampak sosio-ekologisnya pun masif: Bank Dunia (2024) mencatat 68% petani gurem korban penyitaan jatuh dalam kategori ultra-poor (kurang dari USD 1,9/hari) akibat kehilangan mata pencaharian.
Erosi pengetahuan lokal terjadi seiring punahnya sistem ngarai (rotasi lahan tradisional Sunda) dan parak (agroforestri Minang). Penyitaan tanah masyarakat adat juga memicu degradasi lingkungan, 420.000 hektar tanah sitaan dikonversi untuk monokultur sawit (Walhi, 2023), dan penurunan keanekaragaman hayati dengan hilangnya 142 spesies endemik di eks-lahan sengketa (BRIN, 2024).
Kritik teoretis dari Weber hingga Foucault menyingkap akar diskriminasi ini. Instrumental rationality Weber menjelaskan mengapa birokrasi memilih target “low-risk high-compliance”: petani kecil lebih mudah diintimidasi ketimbang korporasi bermodal hukum kuat.
Analisis Foucault dalam Discipline and Punish (1975) melengkapi dengan konsep biopower, negara mengontrol tubuh sosial melalui tiga mekanisme: spatial partitioning (pemetaan sepihak), normalizing judgment (stigma “malas” pada petani), dan examination (verifikasi administratif sebagai ritual kekuasaan). Realitas ini menegaskan: ketika negara menyita tanah petani gurem 0,3 hektar sambil membiarkan konglomerat menganggurkan 50.000 hektar, yang bekerja bukan hukum, melainkan hierarki kekuasaan yang memperpanjang warisan kolonial.
Paradoks Reforma Agraria, Antara Teks dan Konteks
Tiga paradoks fundamental menggerogoti kebijakan pertanahan Indonesia, mengekspos jurang menganga antara retorika konstitusional dan praktik kekuasaan yang timpang. Paradoks pertama bersifat legal dan terwujud dalam standar ganda pengawasan lahan yang sistematis.
Data Badan Pertanahan Nasional (2023) mengungkapkan negara secara aktif menyita 12.350 hektar lahan “nganggur” milik rakyat, namun secara ironis membiarkan 8,3 juta hektar lahan Hak Guna Usaha (HGU) korporasi yang tidak produktif, luas yang setara dengan 10% Pulau Jawa. Lebih memprihatinkan lagi, 76% lahan korporasi idle tersebut dikuasai oligarki perkebunan menurut investigasi Indonesia Corruption Watch (2024).
Asimetri regulasi ini termanifestasi melalui perbedaan perlakuan hukum yang tajam: petani gurem dikenai sanksi berat berdasarkan Peraturan Menteri ATR No. 18/2021 yang memungkinkan pencabutan hak dalam dua tahun, sementara korporasi dilindungi oleh Pasal 15 UU Penanaman Modal yang memberi kelonggaran hingga lima tahun.
Unggun Priyono (2019) dalam analisis hukum kritisnya menyebut praktik ini sebagai “hukum yang bekerja timpang: rigid untuk wong cilik, elastis untuk pemilik modal”. Dampak sistemiknya terlihat dari alih fungsi 1,2 juta hektar lahan petani untuk Proyek Strategis Nasional 2020-2024, sementara lahan korporasi idle dibiarkan tanpa intervensi berarti.
Paradoks kedua bersifat sosial dan terwujud melalui kekerasan birokrasi terhadap sistem pengetahuan lokal. Di Halmahera, masyarakat adat Togutil dipaksa membuktikan kepemilikan tanah leluhur dengan sertifikat, sebuah konsep asing yang bertentangan dengan sistem hukum adat mereka yang mengenal doro-dodara (penetapan batas alam berbasis sungai dan bukit).
Padahal, hanya 21% wilayah adat seluruh Indonesia yang terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (2024). Menurut James Scott (1998), praktik ini merupakan bagian dari “proyek legibilitas” negara yang memaksa masyarakat masuk dalam kotak administratif, sekaligus menghancurkan epistemologi spasial adat.
Sylvia Tiwon (2000) menyebutnya sebagai “birokratisasi ruang hidup”, bentuk kolonialisme baru melalui birokrasi. Dampak kulturalnya terasa nyata di Sulawesi Tengah, di mana 47% sengketa agraria bersumber dari ketidakcocokan sistem panili (tanda batas tradisional Bugis) dengan persyaratan administratif BPN.
Paradoks ketiga bersifat ekologis dan menunjukkan kebutaan negara terhadap sistem regeneratif tradisional. Kebijakan pertanahan secara keliru menyamakan lahan bera (masa istirahat ekologis) dengan lahan “nganggur”. Padahal studi BRIN (2023) yang melanjutkan metodologi LIPI yang saat ini tergabung dalam BRIN, membuktikan sistem fallow period selama 2-5 tahun pada lahan gilir balik masyarakat Dayak justru meningkatkan keanekaragaman hayati hingga 32%.
Arturo Escobar (1996) mengecam pendekatan negara ini sebagai “ekstraktivisme epistemik“, pengabaian terhadap logika regeneratif tradisional demi mengejar produktivisme kapitalistik. Di Sumba, misalnya, tanah tana marapu yang sengaja tidak ditanami selama ritual Pasola demi menjaga keseimbangan kosmologis, secara administratif dicap sebagai lahan nganggur.
Dampak ekologisnya terukur jelas: penyitaan 4.200 hektar lahan bera di Kalimantan (2023) untuk perkebunan sawit memicu penurunan drastis indeks kesuburan tanah dari 85 menjadi 42 hanya dalam delapan bulan menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2024).
Akar ketiga paradoks ini terletak pada logika negara ekstraktif yang dikonseptualisasikan Timothy Mitchell (2002). Pertama, melalui komodifikasi ruang yang mengubah tanah dari entitas sosio-ekologis menjadi komoditas yang bisa disita sewenang-wenang. Kedua, melalui monopoli epistemik yang memaksa sistem pengetahuan lokal tunduk pada standar administratif negara, sehingga memutus mata rantai kearifan ekologis turun-temurun. Ketiga, melalui aliansi korporasi-negara yang diwujudkan dalam temuan majalah Tempo (2024) bahwa 76% pejabat BPN level eselon I-II memiliki kepemilikan saham di perusahaan agribisnis pemegang HGU.
Konfigurasi inilah yang melahirkan krisis legitimasi paling mendasar: ketika negara lebih keras menghukum petani penggarap 0,5 hektar lahan “nganggur” ketimbang korporasi yang menganggurkan 5.000 hektar, ia secara nyata kehilangan mandat moral sebagai pelayan rakyat.
“Ketika paradoks ini dibiarkan, negara bukan hanya gagal menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, tetapi aktif menjadi mesin pemiskinan struktural. Solusinya menuntut rekonstruksi paradigmatik…”
Reformasi Paradigmatik Menuju Keadilan Agraria
Transendensi atas paradoks reforma agraria memerlukan rekonstruksi filosofis yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup, bukan semata komoditas ekonomi.
Langkah pertama adalah pengakuan hak komunal melalui sertifikasi tanah adat sebagai Hak Komunal sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang harus diimplementasikan dengan menghormati mekanisme pewarisan adat secara organik, seperti sistem pusako tinggi di Minangkabau atau tana ulen di Dayak, tanpa intervensi birokrasi yang mendistorsi otoritas kearifan lokal. Pengakuan ini bukan hanya masalah administratif, melainkan restitusi epistemologis terhadap pengetahuan spasial masyarakat adat yang terabaikan selama berabad-abad.
Langkah kedua menuntut redefinisi konsep “lahan nganggur” melalui pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan parameter ekologis seperti masa bera (periode istirahat regeneratif tanah), aspek sosial termasuk tanah ritual dan pemakaman leluhur, serta faktor ekonomi berupa akses pasar dan infrastruktur. Pendefinisian ulang ini harus mengadopsi prinsip zoning kultural sebagaimana diusulkan antropolog Tania Murray Li (2014), di mana suatu lahan dianggap “produktif” bukan hanya berdasarkan output ekonomi, tetapi juga fungsi sosio-kosmologisnya, seperti tanah tana marapu di Sumba yang sengaja tidak ditanami selama ritual Pasola demi menjaga harmoni kosmik.
Langkah ketiga membangun hierarki sanksi proporsional berbasis prinsip keadilan restoratif. Mekanisme teguran lisan dan tertulis harus menjadi pintu masuk dialog partisipatif sebelum penjatuhan denda progresif yang disesuaikan dengan skala kepemilikan dan kemampuan ekonomi pelaku. Tahap akhir alih fungsi lahan wajib mengutamakan kepentingan publik, seperti lumbung pangan komunitas atau hutan kota, bukan komersialisasi kepada korporasi. Model ini terinspirasi dari mekanisme gala-gala (sanksi adat) di Minangkabau yang lebih menekankan pemulihan daripada pemidanaan.
Langkah keempat meniscayakan Audit Agraria Nasional menyeluruh untuk membongkar kepemilikan lahan idle korporasi. Audit harus dimulai dari pelaku dominan dengan kuasa lahan >100 hektar, melacak jejak kepemilikan silang antara pejabat publik dan perusahaan agribisnis, serta mempublikasikan temuan secara real-time melalui platform digital terbuka. Pendekatan ini mengadopsi model agrarian transparency index yang sukses diterapkan di Kolombia pasca-konflik FARC.
Langkah kelima mengharuskan pembentukan Dewan Pertanahan Independen beranggotakan antropolog, tokoh adat, ekolog, dan akademisi lintas disiplin. Dewan ini berfungsi sebagai watchdog kebijakan dengan kewenangan mengajukan judicial review, menyusun indeks kerentanan agraria, serta menjadi mediator konflik berbasis pendekatan kultural. Keberadaannya merupakan antitesis dari model birokrasi sentralistik yang selama ini mengabaikan suara dari bawah.
Kelima langkah ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan gerakan dekolonisasi pengetahuan untuk mengembalikan makna tanah sebagai dosa aan (ibu bumi) dalam kosmologi masyarakat agraris Nusantara, tempat manusia bukan sebagai pemilik, tetapi bagian dari mata rantai kehidupan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Perlu Ada Reklamasi Kedaulatan
Pernyataan pejabat publik tentang kepemilikan mutlak negara atas tanah bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan gejala patologi kekuasaan kronis, ketika negara melupakan asal-usul genealogisnya sebagai entitas yang lahir dari rahim kedaulatan rakyat.
Konstitusi, dalam perspektif filsafat politik Rousseau dan Locke, bukanlah teks mati yang beku, melainkan kontrak sosial yang hidup, sebuah dokumen organik yang harus dibaca melalui dialektika zaman dan nurani kolektif. Jika Pasal 33 UUD 1945 dimaknai secara literer sebagai legitimasi kepemilikan mutlak negara, maka kita sedang membangun neo-feodalisme abad ke-21: suatu tatanan di mana pemerintah bertransformasi menjadi tuan tanah, sementara rakyat, yang seharusnya pemilik kedaulatan, direduksi menjadi penyewa di negeri sendiri.
Klaim “negara pemilik tanah” merupakan pembajakan ontologis terhadap relasi sakral manusia dan ruang hidupnya. Mircea Eliade dalam The Sacred and the Profane (1957) mengingatkan: tanah bagi masyarakat tradisional adalah axis mundi, poros kosmis yang menghubungkan manusia, leluhur, dan alam transenden.
Ketika negara mengklaim hak kreasi atas tanah, sebagaimana tersirat dalam retorika “leluhur tidak bisa membuat tanah”, ia melakukan dosa epistemik: mengingkari fakta bahwa tanah adalah palimpsest sejarah rakyat (Derrida) yang mencatat jejak kerja, penderitaan, dan memori kolektif lintas generasi.
Konsekuensi paling berbahaya dari klaim ini adalah erosi legitimasi negara. Max Weber dalam Politics as a Vocation (1919) menegaskan: otoritas negara bertumpu pada kepercayaan moral (legitimacy), bukan semata paksaan (coercion).
Ketika negara lebih sigap menyita tanah petani miskin ketimbang menindak lahan nganggur korporasi, ketika pejabatnya menjadi pemegang saham perusahaan pemilik HGU, maka negara kehilangan mandat etis sebagai pelayan publik. Jürgen Habermas akan menyebut situasi ini sebagai krisis legitimasi sistemik: saat kebijakan publik tak lagi mencerminkan kepentingan umum, melainkan logika akumulasi kapital.
Dalam konteks inilah, pernyataan penutup penulis, “Negara tak pernah menciptakan tanah; tapi hanya mengelola amanat kedaulatan rakyat”, menjadi kredo penegasan ulang fondasi republik. Tanah bukan ciptaan negara, melainkan pra-kondisi eksistensi kebangsaan yang harus dikelola sebagai amanat. Ketika klaim “pemilik mutlak” diucapkan pejabat, di situlah terjadi pembunuhan metaforis terhadap jiwa konstitusi: penghianatan terhadap sumpah “untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945.
Tantangan kita kini adalah reklamasi kedaulatan simbolik: mengembalikan tanah ke pangkuan epistemologi kerakyatan, di mana nilai guna sosial lebih tinggi daripada nilai tukar, di mana hubungan kultural lebih sakral daripada sertifikat, dan di mana negara hadir bukan sebagai tuan, melainkan pelayan yang setia pada amanat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
“Di ujung pertarungan makna ini, pilihannya jelas: kembali ke roh konstitusi yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup rakyat, atau meneruskan warisan domeinverklaring yang mengubah negara menjadi tuan tanah.”
Penulis; Fajar Budhi Wibowo – Pemerhati Kebijakan Publik – Koordinator LSM KOMPAS (Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi) dan peneliti konflik agraria di 17 provinsi.