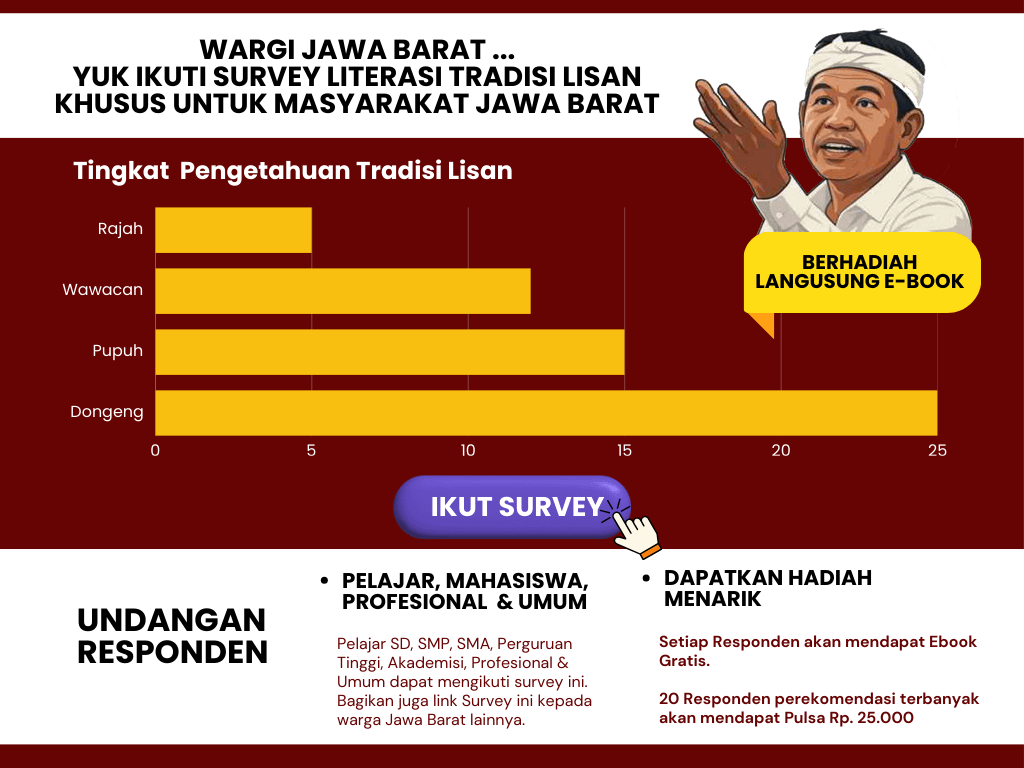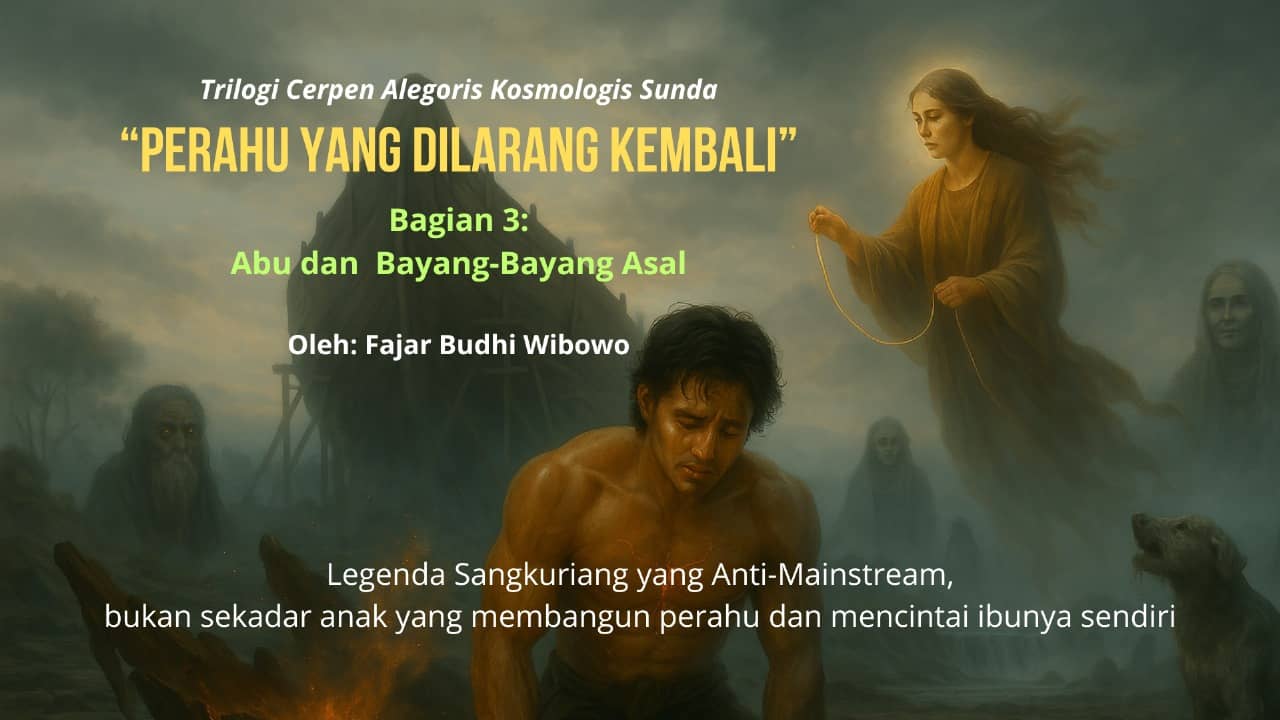Di rumah cahayanya yang terbuat dari benang fajar, Dayang Sumbi duduk, tenunannya compang-camping bagaikan lukisan langit yang robek. Benang waktu yang ia pegang kini berat, namun matanya memancarkan ketenangan purba, seolah ia telah melihat kelahiran dan kematian cerita ini sejak bumi masih muda.
Burung titu tutul kembali dari reruntuhan, sayapnya berkilau seperti air mata bintang, berbisik dengan nada penuh rahasia:
“Anak seuneu moal eureun, tapi wanci moal ngantosan. Asal anjeun nyanyi dina kalangkangna.”
(Anak api takkan berhenti, tapi waktu takkan menunggu. Asalmu bernyanyi di bayangannya.)
Orang Tua Lembah berkumpul di bawah pohon tertua, daun-daunnya gugur seperti air mata zaman. Ki Jarwa Dipa memegang tongkat akarnya, matanya berkobar seperti nyala burung hantu di malam kelam.
“Bumi panca tengah geus ngahariring kawih karuhun, tapi anak seuneu teu ngadéngékeun,” katanya.
(Bumi telah menyanyikan lagu leluhur, tapi anak api tak mendengarkan.)
Suaranya menggema seperti guntur di dasar bumi.
Nyi Endang Palay meniup serulingnya, nadanya lembut namun mengiris jiwa, seperti doa untuk hujan yang telah lama pergi.
“Cai geus ngalir deui, tapi haté anak seuneu tetep garing, siga anu moal narima cai panon mata langit,” ujarnya.
(Air telah mengalir kembali, tapi hati anak api tetap kering, seolah menolak air mata langit.)
Si Panyileukan, dengan senyum tujuh ribu tahun yang penuh teka-teki, menggambar lingkaran di tanah, cahayanya samar seperti bintang yang tersesat di siang bolong.
“Anak seuneu ngudag kalangkang, tapi kalangkangna ngawih asal-usulna sorangan,” katanya, tawanya menggema seperti lonceng purba.
(Anak api mengejar bayangan, tapi bayangannya menyanyikan asal-usulnya sendiri.)
Mereka tahu, Sangkuriang tidak akan menyerah, namun waktu telah merajut nasibnya dengan benang yang tak bisa diputus.
Di tengah reruntuhan, Sangkuriang mengangkat kepalanya, matanya menangkap bayang-bayang di kabut, wajah yang asing namun mengguncang jiwanya, seperti cermin yang retak oleh dosa. Ia menggali lumpur di bawah sisa perahu, tangannya gemetar, mencari sesuatu yang memanggil dari kedalaman bumi.
Tiba-tiba, kabut membentuk sosok lain: seekor anjing dengan mata penuh kesetiaan, darah menetes dari tubuhnya yang samar, dan lolongan pelan menggema seperti tangisan kahyangan yang terluka. Aroma bulu basah menusuk hidungnya, membangkitkan ingatan yang terkubur: panah yang ia lepaskan, darah yang membasahi tangannya, dan jeritan yang menghantui mimpinya.
“Si Tumang…” bisik Sangkuriang.
Dadanya sesak oleh kenangan masa kecil, sosok anjing yang selalu menemaninya berlari di hutan, menjaga langkahnya dengan tatapan penuh kasih.
“Naon anu ku kuring di pilampah ka anjeun, Bapa?” Suaranya patah, seperti pohon yang tumbang di hutan mati.
(Apa yang telah kulakukan padamu, Ayah?)