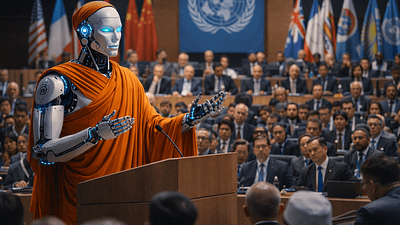SinergiNews – OPINI. Di tanah Pasundan, kebudayaan tidak selalu berbicara melalui bangunan megah atau naskah kuno. Kadang hadir berwujud sebagai tanaman yang berdiri tegak di tepi halaman, sunyi, namun sarat makna. Hanjuang adalah salah satunya. Tumbuh tanpa banyak tuntutan, tetapi memikul tafsir panjang tentang batas, perlindungan, dan martabat ruang hidup orang Sunda.
Secara ilmiah, dunia mengenalnya sebagai Cordyline fruticosa. Namun bagi masyarakat Jawa Barat, hanjuang lebih dari hanya sebatas spesies tropis. Tanaman ini simbol yang hidup dalam ritus, mitos, pengobatan tradisional, pembungkus makanan, penghias upacara, penanda wilayah, pewarna alami, hingga kisah-kisah rakyat yang membentuk jati diri kolektif. Kehadirannya bukan tempelan dekoratif, melainkan bagian dari sistem makna yang membingkai cara pandang terhadap alam dan kehidupan.
Hanjuang dan Kosmologi Batas
Dalam kosmologi Sunda, ruang tidak dipahami secara datar. Ada lapis-lapis nilai yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Yang Maha Kuasa. Rumah bukan hanya tempat berteduh, keberadaaanya adalah pusat kehidupan yang dijaga kehormatannya. Di ambang inilah hanjuang sering ditanam, di dekat pintu, di sisi gerbang, di sudut, bahkan di pemakaman, yang menandai peralihan dari luar ke dalam.
Penempatan tersebut bukan kebetulan. Hanjuang menjadi penanda batas, siapa pun yang melangkah melewatinya akan diingatkan untuk menjaga sikap. Batas bukanlah tembok pemisah, melainkan garis etika. Hanjuang mengajarkan bahwa setiap ruang memiliki adab. Tanpa batas, kehidupan menjadi liar, dengan batas, lahirlah keteraturan dan rasa hormat.
Daunnya yang runcing dan menjulang seakan mengarah ke langit, menandakan orientasi vertikal, manusia tidak hanya hidup di bumi, tetapi juga terhubung dengan nilai-nilai luhur. Akarnya menghujam tanah, simbol bahwa identitas harus bertumpu pada pijakan yang kuat. Filosofi ini selaras dengan prinsip silih asah, silih asih, silih asuh, saling menguatkan dalam keseimbangan.
Jejak Hidup dalam Ritus dan Keseharian
Hanjuang tidak berhenti sebagai simbol ruang. Tanaman ini hadir dalam berbagai ritus adat, menjadi bagian dari perlengkapan upacara yang sarat makna. Dalam praktik pengobatan tradisional, daunnya dimanfaatkan sebagai ramuan penyembuhan. Di dapur-dapur lama, saat ini kerap menjadi pembungkus makanan, bukan menjadi media yang praktis, tetapi cara menyatukan fungsi dan nilai.
Warna merah keunguan yang khas juga mengandung daya simbolik. Ini melambangkan keberanian, keteguhan, sekaligus perlindungan. Dalam cerita rakyat, hanjuang kadang menjadi saksi perjalanan tokoh-tokoh yang diuji kesetiaannya. Tumbuhan ini hadir sebagai metafora, hidup harus tegak, meski angin datang dari segala arah. masih ingat dengan Babad Hanjuang?
Warisan pengetahuan tentang hanjuang mengalir secara lisan. Tidak ada papan nama atau plakat khusus yang menjelaskan maknanya. Orang tua menanamnya, anak-anak melihat dan menyerap pesan diam-diam. Begitulah kebudayaan bekerja, tanpa banyak slogan, tetapi membentuk karakter secara perlahan.
Modernitas dan Krisis Simbol
Namun zaman bergerak cepat. Halaman rumah menyempit, diganti beton dan pagar besi. Tanaman-tanaman lokal tersisih oleh tren hortikultura instan. Hanjuang yang dulu berdiri sebagai penjaga batas kini kerap dianggap kuno. Modernitas menawarkan efisiensi, tetapi sering lupa menyisakan ruang bagi simbol.
Krisis yang terjadi bukan hanya pada tumbuhan, melainkan pada kesadaran. Ketika simbol-simbol lokal ditinggalkan, identitas menjadi rapuh. Kita mudah terpesona oleh budaya luar, tetapi gagap menjelaskan makna dari halaman sendiri. Di titik ini, hanjuang mengajukan pertanyaan diam, apakah kita masih mengenali akar kita?
Dari Tanaman ke Motif Ikonik
Di sinilah pentingnya transformasi makna. Mengangkat hanjuang sebagai motif ikonik Batik Khas Jawa Barat bukan langkah kosmetik. Itu adalah strategi kebudayaan. Sebuah cara cerdas menenun ulang simbol lama ke dalam medium baru yang relevan dengan industri kreatif masa kini.
Motif hanjuang menawarkan garis tegas dan ritme visual yang kuat. Ia dapat dikembangkan menjadi pola batik yang khas, membawa narasi tentang ritus, mitos, dan keseharian masyarakat Sunda. Ketika motif tersebut dikenakan, nilai yang dibawanya ikut bergerak bersama tubuh pemakainya.
Langkah ini bukan hanya soal desain. Pergerakan yang menjadi pernyataan sadar bahwa warisan tidak dibiarkan membeku sebagai artefak museum. Warisan harus hidup, beradaptasi, dan menggerakkan kebanggaan bersama. Dengan menjadikan hanjuang sebagai identitas visual, Jawa Barat menegaskan keberanian untuk berdiri di atas akar sendiri sembari melangkah ke depan.
Menanam Masa Depan dari Akar Tradisi
Hanjuang mengajarkan satu hal sederhana namun mendalam, untuk menjulang tinggi, seseorang harus berakar kuat. Dalam konteks kebudayaan, akar itu adalah nilai, ingatan, dan simbol yang dirawat secara kolektif. Tanpa akar, pertumbuhan hanya ilusi, tampak tinggi, tetapi mudah tumbang.
Maka, menanam hanjuang kembali di pekarangan, menghadirkannya dalam ruang publik, atau mengolahnya menjadi motif batik bukan tindakan romantik belaka. Itu adalah investasi identitas. Sebuah upaya meneguhkan bahwa Sunda dan Jawa Barat memiliki bahasa simboliknya sendiri, bahasa yang tidak perlu berteriak, karena kekuatannya lahir dari kedalaman makna.
Jika suatu hari hanjuang kembali tegak di halaman-halaman rumah, di taman kota, dan di lembar-lembar batik yang dikenakan dengan bangga, itu menandakan satu hal, bahwa masyarakat memilih berdamai dengan akarnya. Dunia boleh berubah cepat. Teknologi boleh melesat jauh. Namun selama akar tetap terjaga, pertumbuhan akan memiliki arah.
Dan seperti hanjuang yang menjulang tanpa kehilangan pijakan, kebudayaan Sunda pun akan terus tumbuh anggun, tegas, dan tak tercerabut oleh zaman.***
Oleh: Fajar Budhi Wibowo (Pusat Studi Budaya dan Sejarah “Sanghyang Hawu” – Etno Sains Nusantara – Dewan Kebudayaan Kota Cimahi)