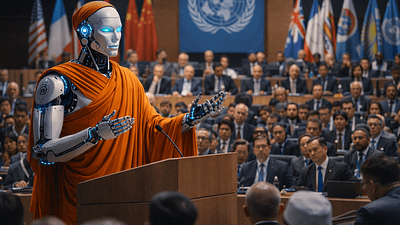SinergiNews – Kab. Bandung. Kebudayaan tidak selalu runtuh oleh gempuran besar. Sering kali, mati pelan, oleh kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Tulisan ini adalah catatan kecil tentang ingatan, tangan, dan cara kita memperlakukan makanan
Plastik yang dipilih karena praktis. Kemasan sekali pakai yang dianggap kemajuan.
Efisiensi yang dipuja tanpa sempat bertanya: apa yang dikorbankan?
Di tengah arus itu, sebuah keputusan sunyi diambil setiap pagi di Kantin SDN Cijagra 01, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Keputusan itu berbentuk baso tahu, dibungkus pipiti anyaman bambu, dialasi daun pisang. Bukan nostalgia. Bukan estetika. Melainkan sikap konsitensi kebudayaan.

Kewirausahaan Budaya, Ketika Dagang Memiliki Arah
Dalam diskursus kebijakan, kewirausahaan budaya kerap dipahami secara sempit, sekadar usaha ekonomi yang “bernuansa budaya”. Padahal, secara konseptual, kewirausahaan budaya adalah praktik ekonomi yang menjadikan kebudayaan sebagai sumber nilai, sistem kerja, dan orientasi keberlanjutan.
Apa yang dilakukan Eka Suryani bukan tempelan budaya pada usaha kecil. Sosok ini sedang menjalankan ekonomi berbasis pengetahuan tradisional. Setiap pipiti yang digunakan adalah keputusan produksi. Setiap daun pisang yang dilipat adalah pernyataan nilai. Setiap baso tahu yang disajikan adalah hasil dari sistem yang sadar akan asal-usulnya.
“Kalau semua diganti plastik, lama-lama anak-anak lupa,” ujar Eka. Kalimat itu bukan keluhan. Itu diagnosis kebudayaan.
Dalam antropologi ekonomi, praktik seperti ini disebut embedded economy, ekonomi yang tertanam dalam relasi sosial, etika lokal, dan ingatan kolektif. Dagang tidak berdiri sendiri. Hal ini menyatu dengan cara hidup.
Pipiti dan Daun Pisang sebagai Teknologi Budaya
Pipiti bambu dan daun pisang sering direduksi sebagai simbol tradisi. Padahal, keduanya adalah teknologi budaya, hasil dari akumulasi pengetahuan panjang tentang material, fungsi, dan relasi dengan alam.
Bambu dipilih karena cepat tumbuh, kuat, dan mudah diperbarui. Daun pisang digunakan karena lentur, higienis, memberi aroma, dan kembali ke tanah tanpa menyisakan racun. Ini bukan romantisme masa lalu. Ini logika ekologis yang telah diuji waktu.
Bayangkan, bila muncul alasan tidak menggunakan pipiti karena mahal, cukuplah pakai daun pisang atau daun apapun yang bisa untuk alas atau bungkus makanan, tidak menggunakan plastik. Ketika satu lapak jajanan sekolah mampu meniadakan ribuan kemasan plastik dalam satu tahun ajaran, maka jelas, keberlanjutan tidak selalu menunggu inovasi mahal. Kadang, hal ini hanya menunggu keberanian untuk kembali menggunakan pengetahuan yang telah kita miliki.
Gastronomi sebagai Bahasa Nilai
Dalam kajian gastronomi budaya, makanan dipahami sebagai bahasa, maka ini berbicara tentang kelas sosial, relasi kuasa, hingga etika hidup. Baso tahu pipiti bukan hanya soal rasa. Model ini adalah narasi tentang cara makan yang bermartabat.
Anak-anak mungkin tidak membaca jurnal antropologi. Namun tubuh mereka belajar. Tangan mereka merasakan tekstur bambu. Hidung mereka merekam aroma daun pisang. Ingatan sensorik itu menempel, lalu menetap.
“Ini yang sering kita lupakan,” kata Fajar Budhi Wibowo, penggiat dan pemerhati pengetahuan tradisional. “Kebudayaan tidak diwariskan lewat ceramah, tapi lewat pengalaman berulang. Baso tahu pipiti adalah pendidikan budaya tanpa kelas.”
Dalam pandangan Fajar, praktik Eka adalah contoh paling konkret pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Bukan pelestarian pasif, melainkan kebudayaan yang bekerja, menghasilkan, dan berkelanjutan.
Ekonomi Kecil, Daya Ubah Besar
Sering kali, kebijakan terjebak pada skala. Yang kecil dianggap tidak strategis. Padahal, justru di ruang-ruang kecil, kantin sekolah, pasar rakyat, dapur rumahan, kebudayaan diuji daya tahannya.
Eka Suryani tidak menunggu program. Tidak menunggu insentif. Ibu ini bertindak karena keyakinan bahwa berdagang juga bisa menjadi cara merawat peradaban.
Inilah inti kewirausahaan budaya bukan seberapa besar omzetnya, melainkan seberapa dalam nilainya tertanam.
Refleksi: Masa Depan Tidak Selalu Datang dari Depan
Kita sering membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang baru. Padahal, sering kali masa depan justru datang dari cara lama yang dipilih kembali dengan kesadaran baru.
Sebungkus baso tahu di pipiti bambu mungkin terlihat remeh. Namun di dalamnya tersimpan pertanyaan besar:
apakah kita masih percaya bahwa kebudayaan bisa hidup bersama ekonomi, tanpa saling meniadakan?
Jika jawabannya ya, maka praktik-praktik seperti ini bukan pinggiran. Ia adalah inti.
Dan mungkin, masa depan kebudayaan Indonesia tidak hanya sedang dibicarakan di ruang seminar atau dirumuskan dalam dokumen kebijakan. Mungkin, hal tersebut sedang disiapkan diam-diam, di kantin sekolah, oleh seorang perempuan yang memilih bambu dan daun pisang, ketika dunia memilih plastik.
Catatan Opini Budaya – SinergiNews
SinergiNews memandang praktik baso tahu pipiti sebagai model kewirausahaan budaya yang utuh, berbasis pengetahuan tradisional, berdampak ekologis, dan relevan dengan agenda nasional, mulai dari Dana Indonesiana, ekonomi hijau, hingga pendidikan berkarakter. Di tengah krisis lingkungan dan krisis makna, kebudayaan tidak membutuhkan slogan baru. Ia membutuhkan orang-orang yang berani menjadikannya cara hidup.***